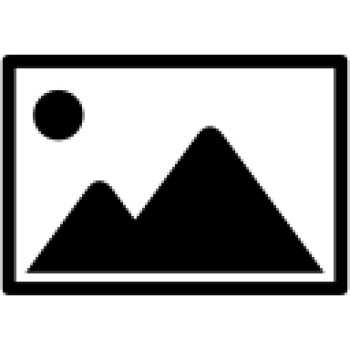Harga Sawit Bakal Tetap Tinggi di 2011
25 Januari 2011
Admin Website
Artikel
3829
Jakarta -
Permintaan minyak sawit global di 2011 tetap akan meningkat akibat
penurunan produksi minyak kedelai. Namun karena tidak diimbangi dengan
produksi yang cukup, harga CPO bakal bertahan di US$ 1.000-1.200/ton.
Demikian disampaikan oleh Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan dalam siaran pers, Senin (24/1/2011).
"Beberapa analis dunia memperkirakan kebutuhan minyak sawit dunia akan bertambah antara 2-3 juta ton pada 2011. Walaupun permintaan naik, diperkirakan suplai minyak sawit tidak dapat mengimbangi permintaan, sehingga harga CPO akan tetap bertahan antara US$ 1.000-1.200/ton sampai semester I-2011," tutur Fadhil.
Meski begitu, Fadhil mengatakan, industri sawit Indonesia mengalami tujuh hambatan utama di 2011. Penambahan produksi minyak sawit dunia diperkirakan mencapai 2,5 juta ton di mana kontribusi produksi CPO Indonesia berkisar antara 1,8-2 juta ton.
Tujuh hambatan tersebut membuat industri sawit akan kesulitan melakukan ekspansi dan atau mengalami penurunan daya saing jika hambatan tersebut tidak dihilangkan.
Hambatan tersebut adalah pertama pelaku sawit menghadapi masalah lahan bagi pengembangan kebun baru yang diakibatkan ketidaktuntasan masalah tata ruang nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).
"Selain, adanya ketidakpastian hukum terhadap status legalitas lahan. Kondisi ini membuat pemegang konsesi dan investor memilih sikap 'wait and see' yang tentu saja akan berdampak kepada tingkat ekspansi lahan," ujar Fadhil.
Kedua, kebijakan moratorium hutan primer dan lahan gambut malahan dapat mempersulit penuntasan masalah lahan yang sebelumnya telah dihadapkan dengan masalah RTRWP. Dalam pandangan Gapki, Inpres mengenai moratorium akan bertabrakan dengan regulasi lain seperti UU Nomor 41 Tahun 1999 mengenai Kehutanan. Atas dasar itulah, kebijakan moratorium menjadi kontraproduktif bagi pengembangan investasi kelapa sawit.
"Meskipun pemerintah menyediakan lahan terdegradasi seluas 35,2 juta ha tetapi status areal tersebut masih meragukan karena termasuk kawasan hutan," jelas Fadhil.
Ketiga, bea keluar CPO yang tinggi dan bersifat progresif seperti berlaku sekarang ini terbukti tidak maksimal untuk menekan volume ekspor CPO dan belum mampu mendorong pengembangan industri hilir dalam negeri.
Sebaliknya, sistem bea keluar diyakini tidak adil bagi produsen bahan baku baik perkebunan negara/swasta maupun petani rakyat karena 'tidak menikmati' kenaikan margin yang seharusnya didapatkan dari tingginya harga CPO dunia saat ini. Jadi tidak tepat apabila bea keluar dijadikan instrumen utama karena sebenarnya industri hilir lebih membutuhkan insentif yang tepat dan menarik.
Keempat, pengembangan perkebunan kelapa sawit yang mengarah ke Indonesia Timur kurang didukung infrastruktur yang memadai seperti pelabuhan. Semestinya terdapat satu pelabuhan ekspor CPO di Kalimantan untuk memudahkan penjualan CPO ke luar negeri. Dengan pertimbangan, total produksi CPO dari wilayah Kalimantan dan Sulawesi telah mencapai 30% dari produksi nasional.
"Diharapkan pula pembangunan klaster industri segera direalisasikan untuk pengembangan industri hilir kelapa sawit," kata Fadhil.
Kelima, pelaku usaha sawit merasa dirugikan dengan penerapan aturan perpajakan mengenai PPn atas produk primer TBS. Pasalnya, PPn TBS selama ini dibebaskan sehingga pajak masukan atas barang-barang faktor produksi tidak bisa dikreditkan dan menjadi beban tambahan. Akibatnya, menimbulkan pajak berganda (double taxation) kepada perusahaan yang terintegrasi (produksi-pengolahan).
Keenam, kampanye anti-sawit tetap berlangsung bahkan ada kemungkinan semakin kuat tekanan yang diberikan kepada pelaku industri sawit. Tema kampanye anti-sawit masih dikaitkan dengan isu perubahan iklim maupun kerusakan lingkungan secara umum.
Rangkaian kampanye anti-sawit ini akan semakin sistematik yang tidak saja dilakukan oleh NGO saja melainkan oleh group consumer tertentu dan beberapa negara di Uni Eropa, lewat pemberlakukan standar baru dalam perdagangan sawit dan menerapkan aturan yang berbentuk non-tariff barier.
Ketujuh, Indonesia harus melakukan program mitigasi perubahan iklim dengan kekuatan sendiri tanpa melibatkan bantuan asing. Pelibatan dana asing hanya akan membuat Indonesia makin tergantung pada negara lain, sementara dana bantuan asing belum tentu memberikan dampak langsung pada penyerapan tenaga kerja dan pengurangan keniskinan.
Mencermati peningkatan permintaan pasar minyak nabati dunia yang terus meningkat dan melihat bahwa semua minyak nabati dunia melakukan ekspansi produksi, maka minyak sawit Indonesia tidak boleh berhenti ekspansi jika tidak mau kehilangan peluang pasar dan kehilangan momentum membangun perekonomian nasional.
"Oleh karena itu, semestinya pemerintah membuat iklim yang kondusif dengan membuat terobosan kebijakan sebagai upaya mengatasi hambatan yang dihadapi pelaku industri sawit nasional," tukas Fadhil.
Demikian disampaikan oleh Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan dalam siaran pers, Senin (24/1/2011).
"Beberapa analis dunia memperkirakan kebutuhan minyak sawit dunia akan bertambah antara 2-3 juta ton pada 2011. Walaupun permintaan naik, diperkirakan suplai minyak sawit tidak dapat mengimbangi permintaan, sehingga harga CPO akan tetap bertahan antara US$ 1.000-1.200/ton sampai semester I-2011," tutur Fadhil.
Meski begitu, Fadhil mengatakan, industri sawit Indonesia mengalami tujuh hambatan utama di 2011. Penambahan produksi minyak sawit dunia diperkirakan mencapai 2,5 juta ton di mana kontribusi produksi CPO Indonesia berkisar antara 1,8-2 juta ton.
Tujuh hambatan tersebut membuat industri sawit akan kesulitan melakukan ekspansi dan atau mengalami penurunan daya saing jika hambatan tersebut tidak dihilangkan.
Hambatan tersebut adalah pertama pelaku sawit menghadapi masalah lahan bagi pengembangan kebun baru yang diakibatkan ketidaktuntasan masalah tata ruang nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).
"Selain, adanya ketidakpastian hukum terhadap status legalitas lahan. Kondisi ini membuat pemegang konsesi dan investor memilih sikap 'wait and see' yang tentu saja akan berdampak kepada tingkat ekspansi lahan," ujar Fadhil.
Kedua, kebijakan moratorium hutan primer dan lahan gambut malahan dapat mempersulit penuntasan masalah lahan yang sebelumnya telah dihadapkan dengan masalah RTRWP. Dalam pandangan Gapki, Inpres mengenai moratorium akan bertabrakan dengan regulasi lain seperti UU Nomor 41 Tahun 1999 mengenai Kehutanan. Atas dasar itulah, kebijakan moratorium menjadi kontraproduktif bagi pengembangan investasi kelapa sawit.
"Meskipun pemerintah menyediakan lahan terdegradasi seluas 35,2 juta ha tetapi status areal tersebut masih meragukan karena termasuk kawasan hutan," jelas Fadhil.
Ketiga, bea keluar CPO yang tinggi dan bersifat progresif seperti berlaku sekarang ini terbukti tidak maksimal untuk menekan volume ekspor CPO dan belum mampu mendorong pengembangan industri hilir dalam negeri.
Sebaliknya, sistem bea keluar diyakini tidak adil bagi produsen bahan baku baik perkebunan negara/swasta maupun petani rakyat karena 'tidak menikmati' kenaikan margin yang seharusnya didapatkan dari tingginya harga CPO dunia saat ini. Jadi tidak tepat apabila bea keluar dijadikan instrumen utama karena sebenarnya industri hilir lebih membutuhkan insentif yang tepat dan menarik.
Keempat, pengembangan perkebunan kelapa sawit yang mengarah ke Indonesia Timur kurang didukung infrastruktur yang memadai seperti pelabuhan. Semestinya terdapat satu pelabuhan ekspor CPO di Kalimantan untuk memudahkan penjualan CPO ke luar negeri. Dengan pertimbangan, total produksi CPO dari wilayah Kalimantan dan Sulawesi telah mencapai 30% dari produksi nasional.
"Diharapkan pula pembangunan klaster industri segera direalisasikan untuk pengembangan industri hilir kelapa sawit," kata Fadhil.
Kelima, pelaku usaha sawit merasa dirugikan dengan penerapan aturan perpajakan mengenai PPn atas produk primer TBS. Pasalnya, PPn TBS selama ini dibebaskan sehingga pajak masukan atas barang-barang faktor produksi tidak bisa dikreditkan dan menjadi beban tambahan. Akibatnya, menimbulkan pajak berganda (double taxation) kepada perusahaan yang terintegrasi (produksi-pengolahan).
Keenam, kampanye anti-sawit tetap berlangsung bahkan ada kemungkinan semakin kuat tekanan yang diberikan kepada pelaku industri sawit. Tema kampanye anti-sawit masih dikaitkan dengan isu perubahan iklim maupun kerusakan lingkungan secara umum.
Rangkaian kampanye anti-sawit ini akan semakin sistematik yang tidak saja dilakukan oleh NGO saja melainkan oleh group consumer tertentu dan beberapa negara di Uni Eropa, lewat pemberlakukan standar baru dalam perdagangan sawit dan menerapkan aturan yang berbentuk non-tariff barier.
Ketujuh, Indonesia harus melakukan program mitigasi perubahan iklim dengan kekuatan sendiri tanpa melibatkan bantuan asing. Pelibatan dana asing hanya akan membuat Indonesia makin tergantung pada negara lain, sementara dana bantuan asing belum tentu memberikan dampak langsung pada penyerapan tenaga kerja dan pengurangan keniskinan.
Mencermati peningkatan permintaan pasar minyak nabati dunia yang terus meningkat dan melihat bahwa semua minyak nabati dunia melakukan ekspansi produksi, maka minyak sawit Indonesia tidak boleh berhenti ekspansi jika tidak mau kehilangan peluang pasar dan kehilangan momentum membangun perekonomian nasional.
"Oleh karena itu, semestinya pemerintah membuat iklim yang kondusif dengan membuat terobosan kebijakan sebagai upaya mengatasi hambatan yang dihadapi pelaku industri sawit nasional," tukas Fadhil.
DIKUTIP DARI DETIK ONLINE, SENIN, 24 JANUARI 2011